Pengertian dan Tata Cara Pemberian Grasi
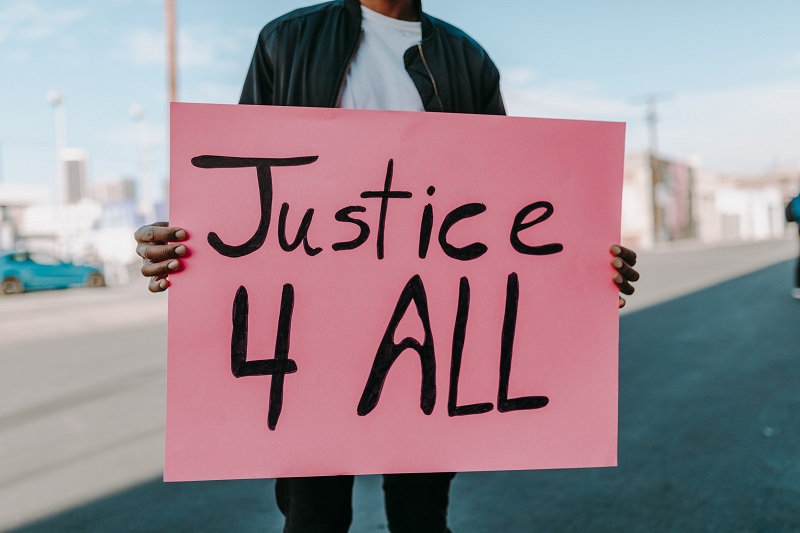
Sebagai Negara yang menganut sistem Pemerintahan Presidensial, Indonesia dipimpin oleh seorang Presiden yang mempunyai otoritas besar dan kuat. Selain sebagai kepala negara dan kepala Pemerintahan, Presiden juga memiliki hak istimewa atau hak eksklusif yang melekat padanya atau yang biasa disebut hak prerogratif.[1] Hak prerogratif secara teoritis diartikan sebagai hak istimewa yang dimiliki oleh lembaga-lembaga tertentu yang bersifat mandiri dan mutlak. Hak prerogratif Presiden membawahi banyak bidang salah satunya adalah bidang yudisial.
Hak prerogratif Presiden dalam bidang yudisial adalah membuat keputusan terkait dengan pemberian Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi (GAAR) bagi mereka yang sedang berhadapan dengan proses hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Merujuk hak prerogratif Presiden yakni Grasi, diberikan terhadap terpidana yang berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi (UU Grasi), dinyatakan bahwa
Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden.
Dalam UU Grasi, permohonan dan pemberian grasi terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (2) 1 UU Grasi yang mengubah ketentuan dalam UU 22/2002 menyebutkan bahwa:
- Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden.
- Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun.
- Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali.
Pembatasan pengajuan permohonan grasi hanya dapat diajukan 1 (satu) kali dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengajuan permohonan grasi dan menghindari pengaturan yang diskriminatif. Pihak yang dapat mengajukan permohonan grasi secara tertulis adalah:
- Terpidana atau kuasa hukumnya;
- Keluarga terpidana dengan persetujuan keluarga yang dimaksud adalah isteri atau suami, anak kandung, orang tua kandung, atau saudara sekandung terpidana;
- Keluarga terpidana, tanpa persetujuan apabila terpidana dijatuhi pidana mati.
Tata cara pengajuan dan penyelesaian permohonan grasi diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 UU Grasi yang menyebutkan bahwa:
Pasal 5:
- Hak mengajukan grasi diberitahukan kepada terpidana oleh hakim atau hakim ketua sidang yang memutus perkara pada tingkat pertama.
- Jika pada waktu putusan pengadilan dijatuhkan terpidana tidak hadir, hak terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh panitera dari pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama.
Pasal 6:
- Permohonan grasi oleh terpidana atau kuasa hukumnya diajukan kepada Presiden.
- Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh keluarga terpidana, dengan persetujuan terpidana.
- Dalam hal terpidana dijatuhi pidana mati, permohonan grasi dapat diajukan oleh keluarga terpidana tanpa persetujuan terpidana.
Pasal 6A:
- Demi kepentingan kemanusiaan dan keadilan, menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk mengajukan permohonan grasi.
- Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang meneliti dan melaksanakan proses pengajuan Grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 6A ayat (1) dan menyampaikan permohonan dimaksud kepada Presiden.
Pasal 7:
- Permohonan grasi dapat diajukan sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.
Pasal 8:
- Permohonan grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diajukan secara tertulis oleh terpidana, kuasa hukumnya, atau keluarganya, kepada Presiden.
- Salinan permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung.
- Permohonan grasi dan salinannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disampaikan oleh terpidana melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana.
- Dalam hal permohonan grasi dan salinannya diajukan melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyampaikan permohonan grasi tersebut kepada Presiden dan salinannya dikirimkan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan grasi dan salinannya.
Dari beberapa pengaturan dalam UU Grasi, ternyata ada satu hal yang pengaturannya tidak tegas, yaitu mengenai tidak ada pembatasan waktu bagi pemohon Grasi. Untuk putusan yang berupa pidana penjara seumur hidup, pidana penjara sementara waktu, dengan tidak adanya pembatasan waktu tersebut tidak akan berpengaruh pada pelaksanaan putusan, tetapi untuk terpidana mati eksekusinya harus menunggu putusan penolakan Grasi dari Presiden. Ketidakjelasan pengaturan tersebut dapat dimanfaatkan oleh terpidana mati untuk menunda eksekusi hukuman.
[1] Sujatmiko & Willy Wibowo, Urgensi Pembentukan Regulasi Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi (Urgency of Formation Regulation Gration, Amnesty, Abolition, and Rehabilitation), Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol. 21 No. 1, Maret 2021
Punya Pertanyaan Tentang Masalah Hukum?
Kirim pertanyaan apapun tentang hukum, tim kami akan dengan maksimal menjawab pertanyaan Anda.
Kirim PertanyaanPengertian dan Tata Cara Pemberian Amnesti
Pemecatan Hakim Konstitusi Aswanto
hukum expert
Hukumexpert.com adalah suatu platform yang memungkinkan penggunanya untuk berinteraksi dengan pengguna lainnya sehingga membuka wawasan dan pikiran bagi mereka yang menggunakannya.
