Hak Bagi Mantan Istri Dalam Perceraian Secara Islam
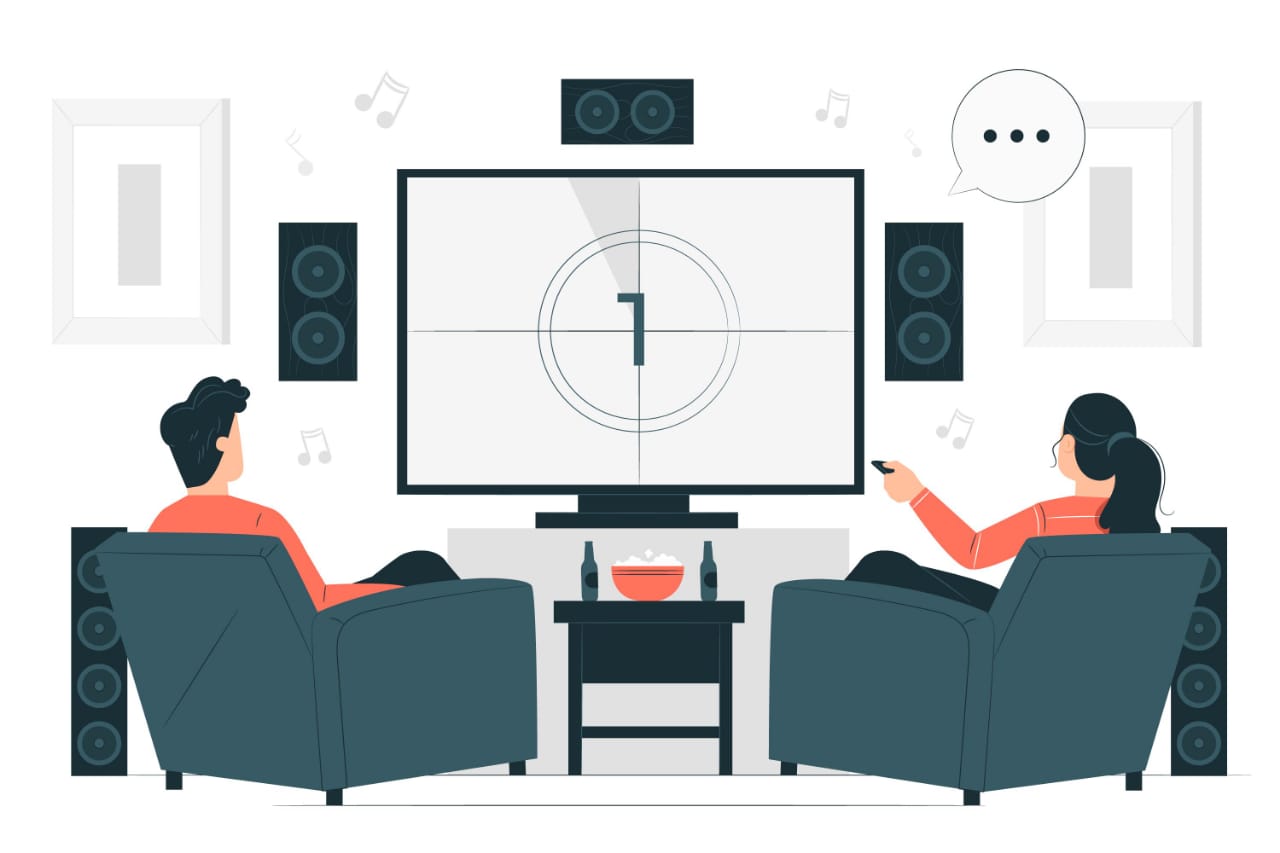
Berdasarkan Pasal 38 Huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut ‘UU Perkawinan’), salah satu alasan putusnya perkawinan adalah perceraian. Dalam perkawinan, bisa saja terjadi permasalahan, konflik atau perselisihan antara suami dan istri yang bermuara pada keinginan untuk memutus perkawinan tersebut atau bercerai.
Perceraian bagi pihak-pihak yang menikah secara agama Islam merupakan wilayah kewenangan Pengadilan Agama untuk memutusnya. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut ‘UU Peradilan Agama’) yang menyatakan:
“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
- perkawinan;
- waris;
- wasiat;
- hibah;
- wakaf;
- zakat;
- infaq;
- shadaqah; dan
- ekonomi syari’ah.
Lebih lanjut, Penjelasan Pasal 49 Huruf a UU Peradilan Agama menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah, diantaranya perceraian karena talak dan gugatan perceraian.
Berdasarkan Pasal 80 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut ‘KHI’), dalam perkawinan yang dilakukan secara agama Islam maka nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri merupakan tanggungan dari suami. Di sisi lain, dalam hal terjadi perceraian dalam perkawinan yang dilakukan secara agama Islam, maka terdapat pula kewajiban-kewajiban mantan suami terhadap mantan istri.
Berdasarkan Pasal 114 KHI, “putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.” Lebih lanjut, Pasal 117 KHI mengatur bahwa “talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.” Apabila istri yang mengajukan gugatan cerai ke pengadilan, maka tidak disebut sebagai talak, melainkan ‘gugatan perceraian’ (Pasal 132 KHI).
Talak dan gugatan perceraian masing-masing memiliki implikasi yang berbeda terhadap kewajiban mantan suami atau hak mantan istri setelah bercerai. Kewajiban mantan suami terhadap mantan istri setelah talak diatur pada Pasal 149 KHI, yaitu:
Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:
- memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba’in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
- melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
- memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun
Bahwa yang dimaksud dengan mut’ah tersebut adalah penghibur atau pemberian dari mantan suami kepada mantan istrinya yang dijatuhi talak baik berupa uang atau benda lainnya. Nafkah Iddah (nafkah dalam masa tunggu), adalah nafkah yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri yang dijatuhi talak selama mantan istri menjalani masa iddah (masa tunggu), kecuali jika mantan istrinya melakukan nusyuz (pembangkangan).[1]
Di samping itu, apabila selama masa perkawinan, mantan suami tidak memberikan nafkah yang merupakan kewajibannya sebagaimana Pasal 80 Ayat (4) KHI, maka mantan suami juga memiliki kewajiban melunasinya yang disebut sebagai nafkah madhiyah. Nafkah madhiyah terdiri atas nafkah madhiyah terhadap istri dan nafkah madhiyah terhadap anak sewaktu anak tersebut belum dewasa dan mandiri (berusia 21 tahun). Biaya Hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak, adalah biaya pemeliharaan dan nafkah untuk anak yang hak hadhanah (hak pemeliharaannya) telah ditetapkan kepada salah satu dari orang tuanya atau keluarga lain yang menggantikannya.[2]
Mengenai besaran nafkah tersebut, didasarkan pada ketentuan Pasal 160 KHI yang menyatakan, “besarnya mut’ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami” juncto Bagian III Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 2 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Badi Pengadilan (selanjutnya disebut ‘SEMA 3/2018’), yang menyatakan:
“Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak”
Berbeda halnya kewajiban mantan suami kepada mantan istri setelah perceraian diatur pada Pasal 156 Huruf d KHI yaitu, “semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).” Mengenai besarannya juga sesuai ketentuan Bagian III Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 2 SEMA 3/2018
Lebih lanjut terdapat talak suami karena li’an yang mana diatur pada Pasal 126 KHI yang menyatakan “li’an terjadi karena suami menuduh isteri berbuat zinah dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya, sedangkan isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.” Perceraian karena li’an maka kewajiban suami mengikuti ketentuan Pasal 162 KHI, yaitu “bilamana li’an terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah.”
Penulis: Mirna R., S.H., M.H., CCD.
Editor: R. Putri J., S.H., M.H., CTL. CLA.
Sumber:
- Kompilasi Hukum Islam;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Badi Pengadilan; dan
- https://pa-surabaya.go.id/halaman/content/hak-perempuan-anak#:~:text=Nafkah%20Madhiyah%20(nafkah%20masa%20lampau,berupa%20uang%20atau%20benda%20lainnya.
[1] https://pa-surabaya.go.id/halaman/content/hak-perempuan-anak#:~:text=Nafkah%20Madhiyah%20(nafkah%20masa%20lampau,berupa%20uang%20atau%20benda%20lainnya.
[2] Ibid.
Punya Pertanyaan Tentang Masalah Hukum?
Kirim pertanyaan apapun tentang hukum, tim kami akan dengan maksimal menjawab pertanyaan Anda.
Kirim Pertanyaanhukum expert
Hukumexpert.com adalah suatu platform yang memungkinkan penggunanya untuk berinteraksi dengan pengguna lainnya sehingga membuka wawasan dan pikiran bagi mereka yang menggunakannya.
